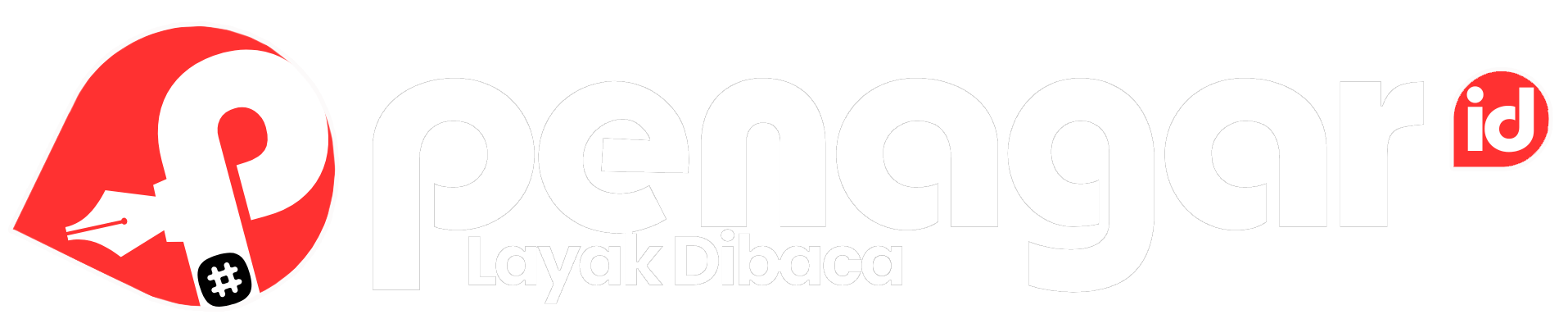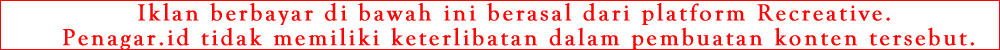Oleh: Iwan Miu
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gajah Mada
* * *
Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dihuni oleh ribuan desa pesisir yang tersebar dari barat hingga timur nusantara. Desa-desa pesisir tidak hanya berperan sebagai penyangga ekologi, tetapi juga merupakan lumbung sumber daya alam, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
Namun, di balik potensi besar tersebut, desa pesisir menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan perhatian serius. Saat ini, banyak desa pesisir berada di ambang krisis akibat masuknya investasi berbasis ekstraksi sumber daya alam yang sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Bone Bolango, khususnya kawasan pesisir yang terletak di ujung timur Provinsi Gorontalo. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya yang melimpah, baik dari sektor perikanan maupun pertanian.
Hasil laut seperti ikan, cumi, dan udang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, disertai hasil perkebunan seperti kelapa, cengkih, dan palawija. Potensi ini sejatinya bisa menjadi modal besar untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Namun, kenyataannya, masuknya aktivitas pertambangan berskala besar telah mengancam keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut. Eksploitasi hutan secara masif terjadi, bahkan di sekitar kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), yang membentang di perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Kawasan yang semestinya dilindungi ini justru menjadi salah satu titik utama eksploitasi tambang, yang berdampak buruk pada ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir di Bone Bolango.
Taman nasional ini cukup dikenal dengan berbagai macam aspek. Di antaranya Biodiversitas: TNBNW memiliki berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies endemik yang khas dari daerah tersebut.
Sayangnya satu kebanggaan daerah ini sudah terlihat jelas kepunahannya dengan perambahan hutan yang begitu besar, sehingga banyak fauna yang terusik dari habitatnya.
Selain itu juga Ekosistem: Taman nasional ini mencakup hutan hujan tropis, pegunungan, serta sungai dan danau, yang mendukung berbagai ekosistem. Eksploitasi berlebihan banyak menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah.
Sungai yang dulunya jernih yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat, saat ini sudah terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Sesuatu hal yang saat ini menghantui masyarakat adalah terjadinya diaspora. Pasalnya jaminan pemerintah akan hal ini belum terencanakan oleh pemerintah saat ini.
Potensi Desa Pesisir
1. Sumber Daya Alam Melimpah
Laut merupakan sumber kehidupan yang vital bagi masyarakat pesisir. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil laut seperti ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut yang menjadi komoditas utama dalam menunjang ekonomi keluarga.
Aktivitas melaut bukan hanya tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga bentuk ketahanan hidup yang terbentuk dari kedekatan masyarakat dengan alam. Di sisi lain, laut juga memberikan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga keberlanjutannya menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir.
Selain penangkapan ikan, wilayah pesisir menyimpan potensi besar dalam budidaya perikanan seperti tambak udang, keramba jaring apung, dan pembudidayaan rumput laut. Potensi ini bisa dikembangkan secara berkelanjutan dengan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal.
Tak kalah penting, keindahan alam pesisir—mulai dari pantai, hutan mangrove, hingga terumbu karang—merupakan daya tarik wisata yang luar biasa. Ekowisata bahari menjadi peluang baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak lingkungan, sekaligus memperkuat identitas budaya maritim Indonesia.
2. Pariwisata Bahari
Desa pesisir memiliki keindahan alam yang luar biasa: pantai berpasir putih, terumbu karang dan budaya lokal yang unik. Jika dikelola dengan baik, desa pesisir dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Keberhasilan dari suatu wilayah tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakatnya, bahkan banyak pemuda mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang berbasis kepemudaan demi untuk menselaraskan visi misi dari pemerintah saat ini.
Barangkali dengan peran pemerintah dalam memberikan informasi serta promosi semacamnya akan menambah nilai jual dan daya tarik banyak banyak pengunjung bahkan sampai dikalangan manca negara.
Faktor penghambat wisata pesisir Bone Bolango di antaranya ialah Aksebilitas terbatas Infrastruktur transportasi (jalan, bandara, pelabuhan) yang belum memadai. Penerbangan internasional terbatas, sehingga wisatawan harus transit melalui Jakarta atau Makassar.
Promosi yang Masih Minim Kurangnya pemasaran destinasi wisata bahari Bone Bolango di pasar internasional. Belum banyak kerja sama dengan agen perjalanan luar negeri. Fasilitas Wisata yang Belum Berkembang Akomodasi (hotel/resort) yang belum memenuhi standar internasional. Keterbatasan restoran, pusat informasi wisata, dan fasilitas pendukung lainnya.
Kurangnya SDM Pariwisata yang Berkualitas Pemandu wisata yang kurang terlatih dan kemampuan bahasa asing yang terbatas.Pelayanan di sektor pariwisata belum optimal. Isu Keamanan dan Kebersihan Persepsi tentang keamanan di kawasan wisata yang perlu ditingkatkan. Kebersihan pantai dan lingkungan yang kurang terjaga.
Regulasi dan Birokrasi Proses perizinan untuk pengembangan wisata yang rumit. Kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendukung pariwisata internasional. Musim dan Kondisi Alam Cuaca buruk atau musim ombak besar yang mengurangi kenyamanan berwisata bahari.
3. Kearifan Lokal dan Budaya Maritim
Masyarakat pesisir di Bone Bolango memiliki beragam kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam hal pelayaran tradisional, teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta pelaksanaan ritual laut yang sarat makna spiritual.
Praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat pesisir. Kearifan lokal ini tumbuh dari pengalaman hidup yang panjang dan telah terbukti menjadi panduan yang relevan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Kearifan lokal masyarakat Bone Bolango merupakan aset budaya yang sangat berharga dan layak untuk dilestarikan. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, nilai-nilai seperti gotong royong, kearifan dalam mengelola sumber daya alam, dan penghormatan terhadap laut sebagai sumber kehidupan perlu diangkat ke permukaan.
Kebanggaan suatu negara tidak hanya diukur dari kemajuan teknologinya, tetapi juga dari bagaimana ia menghargai dan merawat kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, pelestarian budaya pesisir Bone Bolango harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.
Tantangan Desa Pesisir
1. Kemiskinan dan Keterbatasan Infrastruktur
Banyak desa pesisir masih menghadapi kemiskinan struktural. Akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik sering kali terbatas. Hal ini memperlambat pembangunan manusia dan ekonomi. Desa-desa pesisir di Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan struktural.
Masyarakat di wilayah pesisir seperti Kabila Bone, Bone Pantai, dan sekitarnya masih bergantung pada sektor perikanan tradisional yang hasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Minimnya alternatif mata pencaharian dan rendahnya daya beli membuat lingkaran kemiskinan sulit diputus.
Situasi ini diperburuk dengan fluktuasi hasil laut akibat perubahan iklim dan musim tangkap yang tidak menentu.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dasar juga menjadi kendala utama dalam mempercepat pembangunan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih belum merata, bahkan ada wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak atau minimnya transportasi umum.
Fasilitas air bersih dan listrik pun belum sepenuhnya tersedia secara stabil di beberapa desa pesisir. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat serta memperlambat kemajuan ekonomi lokal, sehingga pembangunan di kawasan pesisir Bone Bolango masih tertinggal dibandingkan wilayah lain yang lebih terhubung.
2. Kerusakan Lingkungan dan Iklim
Eksploitasi laut yang berlebihan, abrasi pantai, serta perubahan iklim menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir. Penurunan hasil tangkapan dan naiknya permukaan laut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hidup masyarakat pesisir.
Wilayah pesisir Bone Bolango kini menghadapi tantangan serius akibat kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Eksploitasi laut secara berlebihan, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan penangkapan ikan di luar musim, telah menyebabkan penurunan populasi ikan di perairan sekitar. Akibatnya, nelayan lokal semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harian.
Praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan ini tidak hanya merugikan ekosistem laut, tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Selain itu, abrasi pantai menjadi persoalan nyata di beberapa titik pesisir Bone Bolango. Penggundulan mangrove dan pembangunan tanpa kajian lingkungan memperparah pengikisan garis pantai. Tanah-tanah produktif dan pemukiman warga terancam tenggelam atau rusak akibat hempasan ombak yang semakin kuat.
Naiknya permukaan laut sebagai dampak perubahan iklim global juga meningkatkan risiko banjir rob dan memperpendek waktu melaut bagi nelayan karena kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Situasi ini membuat masyarakat pesisir berada dalam tekanan ekonomi dan ekologis secara bersamaan.
Menghadapi kondisi ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang terencana dan berbasis masyarakat. Program rehabilitasi mangrove, pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, serta edukasi tentang perubahan iklim perlu digalakkan.
Pemerintah daerah Bone Bolango bersama akademisi, LSM, dan komunitas nelayan harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perlindungan pesisir yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa upaya kolektif ini, kerusakan lingkungan akan terus memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir di masa mendatang.
3. Ketimpangan Akses dan Pemasaran
Produk perikanan dan hasil laut seringkali dijual dalam kondisi mentah dengan harga rendah. Akses pasar yang terbatas dan minimnya pengolahan hasil laut membuat nelayan tetap berada di posisi yang lemah dalam rantai nilai ekonomi.
Di wilayah pesisir Bone Bolango, seperti Kecamatan Kabila Bone , Bone Pantai, Bulawa, Bone Raya, Bone, nelayan masih menghadapi ketimpangan akses pasar yang signifikan. Hasil tangkapan laut seperti ikan, cumi, dan udang umumnya dijual dalam kondisi mentah tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
Karena tidak adanya fasilitas penyimpanan dingin atau unit pengolahan hasil perikanan di tingkat desa, para nelayan terpaksa menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak dengan harga yang rendah. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan keuntungan yang layak, meskipun jumlah tangkapan cukup banyak.
Minimnya akses terhadap pasar regional maupun nasional semakin memperlemah posisi tawar nelayan pesisir Bone Bolango dalam rantai nilai ekonomi. Ketergantungan pada jalur distribusi konvensional, kurangnya sarana transportasi memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital menjadi penghambat utama.
Padahal, jika hasil laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asap, abon ikan, atau keripik hasil laut, maka pendapatan nelayan bisa meningkat secara signifikan.
Oleh karena itu, diperlukan dukungan konkret dari pemerintah daerah, seperti pelatihan kewirausahaan, pembangunan fasilitas pengolahan, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas agar nelayan tidak terus berada di posisi yang terpinggirkan.
4. Kurangnya Regenerasi Nelayan
Profesi nelayan mulai ditinggalkan oleh generasi muda karena dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi. Padahal, nelayan adalah profesi strategis dalam ketahanan pangan nasional. Di wilayah pesisir Bone Bolango, profesi nelayan perlahan mulai kehilangan daya tarik di mata generasi muda.
Banyak anak muda lebih memilih merantau ke kota atau mencari pekerjaan lain yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Kondisi ini menjadi sinyal bahaya bagi keberlangsungan tradisi maritim yang telah diwariskan secara turun-temurun. Profesi nelayan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang membanggakan, melainkan sebagai pilihan terakhir karena penghasilannya yang tidak menentu serta beban kerja yang berat.
Padahal, nelayan merupakan aktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan protein hewani dari laut. Ketika jumlah nelayan menurun dan generasi penerus enggan melanjutkan profesi ini, maka potensi produksi perikanan pun terancam menurun.
Di Bone Bolango, banyak nelayan usia lanjut masih melaut sendiri tanpa bantuan generasi muda. Selain menyebabkan penurunan produktivitas, kondisi ini juga memperbesar ketimpangan antar generasi serta memperlambat adopsi teknologi baru di sektor perikanan.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi khusus yang dapat mendorong minat generasi muda terhadap profesi nelayan. Pemerintah daerah Bone Bolango perlu menyediakan pelatihan kewirausahaan maritim, akses pembiayaan yang mudah, serta memperkenalkan teknologi modern yang dapat membuat aktivitas melaut lebih efisien dan menarik.
Selain itu, penguatan pendidikan vokasi kelautan dan pembentukan komunitas nelayan muda bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan dan budaya pesisir di Bone Bolango.
Solusi dan Rekomendasi
1. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas
Mendorong pembentukan koperasi nelayan, pelatihan pengolahan hasil laut, serta penguatan BUMDes untuk mengelola sektor kelautan secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya ekonomi lokal, termasuk melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Desa dapat mengembangkan pariwisata berbasis komunitas (misalnya: ekowisata, wisata bahari). Saat ini banyak pemerintah desa terlena dengan adanya dana desa DD dan ADD sebagai tonggak dalam perkembangan desa. Akan tetapi mereka tidak memperhatikan kebermanfaatan BUMDes yang memberikan begitu besar kontribusi dalam PAD ( Pendapatan Asli Desa).
Oleh karena itu, BUMDes perlu perhatian besar dalam tatanan pemerintahan desa untuk menopang keuangan desa dengan melibatkan kreatifitas dan inovasi pada tataran kepemudaan.
Selain itu juga, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Desa Wisata Panduan pengembangan desa wisata dengan melibatkan komunitas lokal. Peraturan ini menjadi panduan resmi pemerintah Indonesia dalam pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal, termasuk destinasi wisata bahari seperti di Bone Bolango.
Ini bertujuan Memberikan acuan standar pengelolaan desa wisata yang melibatkan komunitas lokal. Memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan, dengan prinsip ekonomi kerakyatan (sesuai UUD 1945 Pasal 33). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan UMKM, budaya lokal, dan pelestarian lingkungan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Vokasional
Memberikan akses pendidikan berbasis potensi lokal dan pelatihan keterampilan teknis bagi generasi muda di desa pesisir. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa-desa pesisir Bone Bolango sangat bergantung pada akses terhadap pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Sayangnya, akses pendidikan di wilayah pesisir seperti Kabila Bone, Bone Pantai, Bulawa dan sekitarnya masih terbatas, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar. Untuk itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang kontekstual, yang mengintegrasikan kearifan lokal dan potensi maritim, seperti perikanan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari.
Dengan begitu, generasi muda tidak hanya mendapatkan ilmu akademis, tetapi juga keterampilan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pelatihan vokasional menjadi langkah strategis untuk membekali pemuda pesisir Bone Bolango dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja maupun wirausaha lokal. Program pelatihan seperti budidaya rumput laut, teknik pengolahan ikan, pembuatan produk turunan laut, serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sangat relevan untuk dikembangkan.
Jika pelatihan ini dikombinasikan dengan penguatan digitalisasi dan pemasaran online, maka generasi muda akan lebih siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi desa mereka sendiri. Pendidikan berbasis potensi lokal bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga menjaga keberlanjutan budaya dan ekonomi pesisir.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi
Digitalisasi pemasaran hasil laut dan penguatan sistem informasi kelautan sangat penting untuk mendukung efisiensi produksi serta akses pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Bone Bolango.
Di era serba digital saat ini, pemasaran hasil laut tidak lagi harus bergantung pada tengkulak atau pasar lokal semata. Melalui platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi pemasaran berbasis lokal, nelayan dan pelaku usaha kecil dapat menjual produk mereka langsung ke konsumen dengan jangkauan yang lebih luas.
Dengan begitu, margin keuntungan bisa lebih besar, dan posisi tawar masyarakat pesisir pun meningkat.
Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur jaringan internet, rendahnya literasi digital, hingga kurangnya pelatihan teknis bagi masyarakat pesisir.
Di Bone Bolango, banyak nelayan yang belum terbiasa menggunakan smartphone secara maksimal untuk kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan pelatihan digitalisasi serta sarana pendukung seperti internet desa, perangkat teknologi, dan pendampingan berkelanjutan.
Selain untuk pemasaran, digitalisasi juga penting dalam penguatan sistem informasi kelautan, seperti prediksi cuaca, titik lokasi ikan, dan manajemen hasil tangkapan. Akses terhadap informasi yang akurat dan real-time dapat membantu nelayan meningkatkan efisiensi dan keamanan saat melaut.
Dengan memanfaatkan teknologi ini, masyarakat pesisir Bone Bolango tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga aktor aktif dalam pengelolaan sumber daya laut secara modern, cerdas, dan berkelanjutan.
4. Perlindungan Ekologis dan Adaptasi Iklim
Program restorasi mangrove, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim harus dijalankan bersama antara pemerintah dan komunitas lokal. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir Bone Bolango.
Naiknya permukaan laut, abrasi pantai, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove mengancam keberlangsungan ekonomi dan tempat tinggal warga. Untuk menghadapi tantangan ini, upaya perlindungan ekologis tidak bisa ditunda.
Salah satu langkah penting adalah melakukan restorasi ekosistem pesisir, khususnya mangrove, yang berfungsi sebagai pelindung alami dari gelombang dan intrusi air laut.
Restorasi mangrove di wilayah pesisir seperti Kabila Bone dan sekitarnya bukan hanya berdampak ekologis, tetapi juga sosial-ekonomi. Mangrove yang tumbuh dengan baik dapat menjadi habitat ikan, udang, dan kepiting, yang menunjang mata pencaharian nelayan.
Selain itu, kegiatan penanaman mangrove yang melibatkan masyarakat setempat dapat memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan. Program ini sebaiknya tidak hanya bersifat proyek sesaat, tetapi dirancang sebagai inisiatif berkelanjutan dengan dukungan pendidikan lingkungan dan insentif ekonomi.
Penting juga untuk mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat, di mana komunitas lokal menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pemerintah daerah Bone Bolango bersama lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu merancang program pelatihan, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang kuat, masyarakat pesisir tidak hanya bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menjaga keseimbangan antara alam dan pembangunan.
5. Pemerintah sebagai Problem Solving
Pemerintah diharapkan dapat hadir lebih aktif dan responsif dalam menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir Bone Bolango. Melalui kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat, desa-desa pesisir dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.
Harapan besar disematkan pada pemerintah daerah terkhusus Bapak Bupati Drs. H Ismet Mile, M.M. dan pusat untuk mendorong program-program restorasi lingkungan, peningkatan kapasitas nelayan dan petani pesisir, serta pembukaan akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pasar.
Perlindungan terhadap kawasan konservasi seperti TNBNW juga harus diperkuat agar eksploitasi sumber daya alam tidak lagi mengorbankan masa depan masyarakat lokal. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, pesisir Bone Bolango dapat bangkit menjadi wilayah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
Harapan besar ini seperti tertuang dalam janji Bupati Drs. H Ismet Mile, M.M. dan Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu dalam:
Visi
“Menuju Bone Bolango Unggul, Maju dan Sejahtera”
Misi
– Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Bone Bolango
yang unggul dan berbudaya
– Meningkatnya penghidupan sektor ekonomi yang layak
– Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI
Program Unggulan:
– Pengadaan sapi
– Tersedianya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memadai dan memfasilitasi rakyat dalam pengurusan izin pertambangan rakyat
– Peningkatan tunjangan kinerja PNS, Pemangku Adat, Pegawai SARA
– Pembentukan 2.500 lorong garden dan 2.500 lorong wisata
– Pembangunan pelabuhan di wilayah Bone Pesisir
– Desa wisata dan ecotourism
– Pusat Kebudayaan Gorontalo
Semoga ini dapat terealisasi dalam kepemerintahannya.